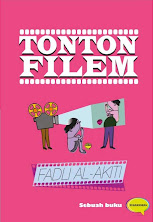NOTA TAMBAHAN (Baca hanya jika sudah menonton filem ini):
Ada banyak "benda" dalam Hanyut, dan hal ini membuatkan filem ini berlapis-lapis (layered) dan seronok dinikmati sebagai wayang, walaupun memang ada kecanggungan dan kelemahannya sebagai mesin logos dan hiburan tontonan.
Terdapat semacam imejan bergerak atau "imej wayang" yang bergerak dwilapis atau mengikut rentak sebelum-selepas yang menyampaikan maksud. Antara perkara yang aku tangkap daripada menontonnya sekali sahaja (kerana itu filem ini berhajat untuk ditonton sekali lagi):
(1) Babak awal filem Hanyut, Mem campak semua perabot ke luar rumah dan bakar. Babak akhir, Almayer bakar seluruh rumahnya.
(2) Babak Nina kembali ke Sambir, dia macam janggal cium ayahnya, hendak ke dahi tapi ke pipi. Babak akhir, dia mencium dahi ayahnya semahu-mahunya, penuh ikhlas.
(3) Babak awal, imej syot Almayer selalunnya dipaparkan dari kepala ke dada duduk/mengiring/bersandar. Babak akhir, Almayer dipaparkan kaki kemudian kepala terbaring (terkulai).
Semua ini bermaksud, dan inilah sinema, lebih-lebih lagi menurut gagasan formalisme, segala objek/imej berubah-bergerak-hidup; melalui transformasi. Yang melakukannya ialah watak-watak, menurut dan menuntut sebab-akibat yang tertera, mungkin ini imbauan Conrad tetapi pastinya - U-Wei. Hal ini disengajakan (perubahan ini) kerana ingin menonjolkan "peralihan" kuasa/dominasi objek/watak/penanda yang diliputii. Objek/imej berubah atau beralih "dominan"nya dengan jelas pada: lelaki(Almayer)-wanita(Mem/Nina), Barat-Timur, menindas-tertindas, rasional-gila, terkawal-chaos. Dalam hal ini juga, secara tersirat, ternyatalah hal imej "terjajah-merdeka", dan lebih jelas lagi: kolonial-pascakolonial. Paling jelas dalam kritikan U-Wei ini, bahawa dunia Timur, yakni Melayu (Islam) tidak dapat dan tidak akan "mengalah" atau terikut, malah menyatakan pendiriannya dengan jelas: mereka akan kekal begitu (degil) sampai bila-bila, walaupun berubah (Orang Kaya Tinggi memakai ala busana Barat) fizikal tetapi jiwanya tetap Melayu, negatif atau positif, itu tidak berubah. Kita lihat sahaja kembali dalam perkara:
(1) Awal, dengan canggung (sebab wanita Melayu takkan berbuat begitu) Mem campak keluar semua perabot kayunya dari dalam rumah (dalam pertengahan, kita mula sedar bahawa barang ini mungkin bukan daripada Almayer pun tetapi ayah angkatnya yang menjadikan Mem ini "minah salleh", maksudnya Mem sedang menolak "western upbringing"nya. Menarik di sini, barang itu juga jika dilihat selapis merupakan barang "material". Maknanya, Mem boleh sahaja atau sudah berani berhadapan untuk membuang materialisme, lebih-lebih lagi baginya, dalam sisi Timur, perabot begitu tidak ada nilai bagi orang Timur/Melayu jika dibandingkan dengan emas dan berlian, yang kita akan ketahui selanjutnya dalam filem ini). Mem campak semua dan bakar di halaman rumahnya, menandakan "naik amuknya" (hal ini tampak tidak logik bagi seorang wanita Melayu, namun ingat, Mem dijaga untuk menjadi Barat, dan dia bergaduh dengan rohaninya setiap hari. Semua ini meletus pada hari suaminya menarik anaknya daripada tangannya untuk diajar jadi orang Barat).
Hal ini menambahkan lagi sikap orang kepadanya sebagai "perempuan gila" kerana perilaku itu tidak dibuat oleh perempuan. Ini dendam dan sumpah Mem. Malah, Mem memang menyumpah suaminya. Apabila "dendam"nya terlunas, dan Almayer kecundang, Almayer, seperti sikap lelaki Latin (atau Mat Salleh?), membakar rumah (keseluruhan) yang diimpikan buat anaknya. Rumah di sini jadi petanda lain, bukan saja impian (dan masa depan Nina), tetapi negara dan kuasa. Jadi, Mem "membuang dan membakar" isi di dalam rumah (unsur yang merosakkan jati dirinya, baginya), tetapi Almayer lebih fatal: jati dirinya sendiri. Hal ini semacam satu kritikan kuat U-Wei pada binari perbandingan Melayu(Timur) lwn. Mat Salleh(Barat), yang menyatakan dengan jelas; orang Melayu dapat membuang pengaruh materialisme/falsafah/pemikiran yang dihalakan kepadanya, namun makna dirinya, asas dirinya, rumahnya (agama-budi-bahasa-adat) tidak terusik, sudah ada asasnya, sudah ada sesuatu yang dipegang, malah dipegang secara rasional-spiritual-emosional (bodohlah Mem jika dia membakar rumahnya sendiri). Malah, dengan mengejutkan lagi, Mem dan Nina yang dipaksa-jadi orang putih akhirnya menjadi Melayu(!) Dengan jelas U-Wei bertutur: segala yang asing datang ke bumi Melayu, akhirnya jadi Melayu juga.
Almayer sebagai wakil Barat, ya memang, berjaya membina material (modal/kekayaan/kuasa/pengaruh) yang gah, namun, kerana kecundang, sanggup menghancurkannya, membakar luluh rumahnya hingga arang. Barat lebih fatalistik, dekaden, dan pesimis, ini berkaitan sangat dengan sikap sekularisme dan humanisme Barat (melihat kekuatan kemanusiaan sepenuhnya). Hal inilah yang diselami oleh de Sade dan Comte akan "pengakhiran" manusia, khususnya Barat dan ketetapan moral dalam "membunuh diri". Malah, dengan jelas, bagi U-Wei, percubaan Barat menuju kepada kehancuran dan sia-sia, berlainan dengan Timur yang mengekalkan suatu pegangan. Hal ini diironikan, malah seperti mengejek-ejek Almayer apabila rumah yang dibakar itu tidak jadi terbakar kerana hujan pun turun. Alam-Melayu memasuki ruang rasional dengan misterius sekali. Menarik untuk diteliti dalam filem ini apabila kita kaitkan pula hal ini dengan Gunung Mas, legenda bagi orang Melayu-Sambir (mereka mempercayainya tetapi mereka tidak ke sana) dan impian tinggi (mencari materialisme) Almayer untuk merebutnya. Adakah pencarian Almayer untuk Gunung Mas ini juga suatu simbol "pencarian ilmu" atau lebih tepat, "pencarian kebenaran" mengikut sisi Barat? Adakah U-Wei mentertawakan kecundangan Almayer untuk itu? Hal ini dapatlah dikaitkan dengan hal yang dibincangkan, mengikut sekali lagi, metode dan pegangan Barat-Timur.
Untuk (2), Aku suka bahagian ini dan dilakukan dengan baik antara Diana-Peter. Pada babak sewaktu Nina mula-mula menemui ayahnya, Nina sengaja diimejkan janggal untuk mencium pipi ayah (tipikal Barat-Belanda?), ini amalan Barat yang diajar cara bermanja dengan ayah/orang tua sewaktu bertemu. Kalau dilihat dengan teliti, awal-awalnya, Nina nyaris-nyaris mahu mencium dahi ayahnya. Mengapa? Pada bahagian akhirnya, dia mencium dahi ayahnya semahu-mahunya. Hal ini janggal dalam gaya Barat. Dalam Melayu-Islam, kita mengucup dahi ayah-ibu-saudara terdekat yang sudah meninggal dan akan berpergian dan tidak kembali lagi. Malah, dahi, tempat kita bersujud ke lantai menjadi tempat ciuman yang layak bagi anak, ini menandakan rasa hormat, tunduk dan sayang kita kepada ibu-bapa-saudara tua. Nina melakukan hal ini pada akhirnya, dengan menyampaikan segala-galanya: dia memaafkan sekali gus memohon maaf ayahnya, dan tahu, menyampaikan; dia tidak akan menemuinya lagi. Hal ini juga, dalam babak kecil ini, kita sedari, Almayer, akhirnya, hancur egonya. Akhirnya, ada satu "amalan" Melayu yang diredakan terhadapnya, malah merangkul semahu-mahunya (walaupun kemudian cepat-cepat memohon anaknya pergi). Di sini, ada sifat kemanusiaan yang menarik dibawa oleh U-Wei dalam pertembungan atau kekacauan binari Barat-Timur; yakni mereka dapat menemui satu "pertalian rohani" dalam memahami antara satu sama lain, walaupun ianya mungkin janggal pada awalnya.
Begitulah. Malah perkara (3) sudah membuktikan, imej wayang (1) dan (2) sudah cukup membuatkan Almayer (Barat) terbaring, kecundang dan terkulai. Pathos bertambah apabila Almayer yang hidup dengan candu (rujuk Once Upon A Time in America tentang apa maksud babak candu ini) menutur dengan perit, "Äku tak boleh lupa (akan dia)." Lupakan siapa? Lupakan apa? Tanah ini. Tanah yang mereka terpaksa lepaskan, cita-cita pencarian (ilmu/penerusan mencari kebenaran), dan jati diri. Amat pesimisnya U-Wei terhadap insan bernama Almayer, disiat-siat dan dihancurkan semangatnya. Namun Conrad juga begitu, seperti jelas penulisannya, malah sangat jelas moralnya: apa yang tidak dikenali usah diusik, dan Barat suka amat mengusiknya dengan metode saintifiknya, lalu begitulah hukuman alam-Timur yang dihadapkan kepadanya, hujan dan puteranya, langsung dia tidak dapat berdiri dan hanya dapat bernostalgik akan hal-hal lepas yang indah di matanya.
Dalam lapisan lain pula, filem ini, menampakkan sikap wayang/sinema U-Wei pada hal sebelum-semasa-masa depan, khususnya wayang Melayu. Namun, hal itu, perlulah dibincangkan dalam entri yang lain pula :)