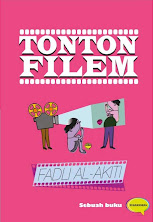Ulasan ini dikhususkan buat Dr. Norman Yusoff yang disanjungi.
Beberapa bulan lepas Secawan Wayang dengan usahasama Dr. Norman menayangkan Maria, dikatakan telefilem pertama TV3, dengan gerak produksi dan gembleng tenaga sekumpulan anak muda yang berkursus di Finas (waktu itu aku rasa, belum lagi ada Akademi Filem dan Akademi Seni Kebangsaan di MATIC). Suhaimi Baba, ya Kak Shumi yang kita kenal dengan pontianak Maya dan filem separa sejarah merdeka dan UMNO itu, dahulunya ialah seorang pembikin filem yang menurut istilah tepatnya: pembikin filem. Filem berdurasi 45 minit itu (yang sememangnya dibuat untuk medium televisyen), dengan mutu suara yang tidak berapa elok (dirakam semula melalui VHS ke medium DVD) menampilkan, sebenarnya, satu cita-cita dan impian mati Suhaimi, rakus dimakan dek sorak suara dan permintaan penonton kontemporari, bermula Selubung (filem sulung Suhaimi) pun lagi.
Secara awal atau impresi pertama, aku tidaklah kagum sangat (bagi Dr. Norman, ini filem terbaik Suhaimi Baba, melangkaui termasuk Layar Lara pun) terhadap hidup Fatimah Abu Bakar waktu muda dengan Mustaffa Noor ala kelas menengah baharu era Dasar Ekonomi Baru, anak-anak muda keluar universiti dan bertugas, bercinta dan kahwin circa 1980-an. Mungkin, kerana aku lebih bersifat dramatik mengada-ngada (aku penyanjung Almodovar sebagai contoh) dan aku teringat pada era 90-an, filem-filem dengan isu kelas menengah dan hal sosial 90-an yang sofistikated sewaktu aku melayan Cerekarama zaman itu (Oh tidah, aku bernostalgia!), malah sudah punya beberapa telefilem-telefilem feminis yang menarik, antara yang aku ingat, saduran Thelma & Louise yang dibikin oleh adik Aziz M. Osman.
Namun, betapa bodohnya aku, apabila menyedari, hey, ini zaman awal 1980-an, zaman orang mengenali wanita hanya daripada air mata Azean Irdawaty, Ogy dan Noorkumalasari. Wanita dalam dunia melodrama Melayu 70-an hingga 80-an (sudah berubahkah apabila kita masih merasai masin air mata Maya dalam Ombak Rindu?) Wanita, era itu, dan mungkin mencapai hiperbolanya yang tertinggi, waktu Perempuan (1988) dalam lakonan mulia Azean. Senang cakap, wanita, bukan sahaja terperosok dalam dunia objek seks lelaki (berapa kali wanita dijadikan objek kutukan kerana seks, objektifikasi janda berhias, ketersampingkan wanita, yang merana sehingga kiamat atas kebodohan dan kekuasaan sistem patriaki?) tetapi menjadi objek material (dipungut/dirogol/dimiliki oleh lelaki) yang perlu melalui satu sumpahan salah tanggap masyarakat. Asyik dan ghairahnya wanita, yang diobjektifikasi sebagai "ibu kau pelacur!" dalam Dia Ibuku, betapa wanita lemah dan bodoh sehingga hilang pertimbangan, lalu mengambil pilihan mabuk, diperkosa oleh para lelaki di bilik hotel dalam Tiada Esok Bagimu. Wanita dalam filem-filem melodrama ini, hanya penyaksi kezaliman, diobjektifikasi dalam bentuk yang seburuk-buruk alam (paling mudah: lemah) - dan banyaknya pasrah "membawa diri" dengan air mata, menyetujui remuk-redam ikonik Sarimah yang terkehel di tepi tiang dalam Ibu Mertuaku.
Jadi, apabila datangnya Maria dan Suhaimi, hal ini (sepatutnya) berubah. Maria membawa suatu persoalan sehari-harian wanita yang bijak, bekerja dan bergerak, meninggalkan sedu-sedan dan objektifikasi materi mudah terhadap peranan dan perwatakan wanita dalam filem era itu. Malah, dengan sengaja, jika kita tonton babak awal Maria, Maria diberikan suara dalaman (dia sedang meluahkan geramnya terhadap suaminya). Ini menjadi suatu filem yang "peribadi" mungkin kepada Suhaimi, dan kemungkinan juga Fatimah. Tapi suara yang dipendam bersuara ini menarik untuk memulakan cerita dua laki bini yang bergaduh. Awal ini sahaja, kita sudah diimpresi bahawa ini filem seperti judulnya, tentang Maria. Tentang wanita (yang moden). Adakah halnya remeh? Ya, tapi permasalahan sehari-harian ini dijadikan fokus, disuarakan oleh protagonis, disampaikan kepada kita untuk diinterpretasi. Dalam hal ini sahaja, Suhaimi dan sekumpulan penulis skrip muda itu telah melakukan pelanggaran tabu objektifikasi wanita: ia bukan sahaja tidak tertindas dengan isu seks, material; ia boleh bercakap, berkata-kata - ia punya roh - pemikiran - intelektual. Warna ton babak itu sahaja biru siluet, gaya yang kita akan tampak digunakan secara ekspresionis berlebihan dalam Selubung (Aziz M. Osman menggunakan gaya sama dalam sebuah cerekarama baik lakonan Ida Nerina). Ada suatu "yang tidak kena" di sini kita bertanya. Kita kemudian dihantarkan beberapa syot imbas kembali sewaktu Fatimah dan Mustaffa "bercintan" ala When Harry Met Sally yang sangat natural dan mundane. Kita terlihat Kee Thuan Chye di situ bertutur lorat Melayu-Inggeris, kawan kepada kedua-duanya.
Kita kemudian, antara babak paling aku suka dalam telefilem ini, babak "diplomasi" bakal ibu mertua Mustaffa, yakni ibu bapa Fatimah, berhubung untuk bercakap tentang "berita tergempar" perkahwinan anak perempuan mereka. Babak ini sungguh intim dan menarik, lebih-lebih lagi melihat fungsi, ekspresi dan bagaimana sang wanita, di sini, ibu Fatimah yang mendominasi ruang keluarganya, melangkaui si suami dalam perancangan dan perutusan nilai. Hal ini dibuat bersahaja tetapi cengkam, juga menyampaikan latar kekuatan kewanitaan dalam dunia Fatimah itu sendiri (kita kembali pada persoalan bijak melangkaui objektifikasi tradisi itu tadi).
Babak pertengahan, waktu Mustaffa-Fatimah sudah kahwin dan mempunyai anak, kita melihat, seakan-akan Mustaffa mula memberontak dengan keadaan "moden" ruang isterinya. Mustaffa tiba-tiba mula menyoal peranan wanita (di rumah) dalam ruang kelas menengah 1980-an. Persoalan material dibawa ke hadapan, tapi dalam keadaan dan persoalan yang lebih moden (dan mengejutkan, masih relevan sekarang). Mustaffa tiba-tiba mula melakukan objektifikasi, awalnya yang kecil dan remeh, dan kemudian menjadi-jadi tingkahnya, menunjukkan ego dan kelelakiannya (yang dirasainya, tercabar dengan nuansa dan bahasa badan isterinya). Waktu ini juga, sebagai sketsa cuit tapi seronok, kita dikenalkan dengan Rosnah Mat Aris sebagai orang gaji yang tidak habis-habis ber"gayut" di telefon. Di sini, saya kagum dengan metafora membina yang sedang dimainkan oleh Suhaimi.
Sepenuhnya, filem ini berkenaan komunikasi. Bagaimana satu pertalian itu kukuh dan bertimbal-balik. Komunikasi juga membentuk "filem". Kita temui ini dalam nuansa dan bahasa badan para pelakonnya. Kita temui ini dalam beberapa babak Fatimah-Mustaffa yang sangat cemerlang (Fatimah, di sini, menjadi antara primadona yang hebat dalam sejarah filem Melayu, moden, sofistikated dan intelektual). Lihat keadaan apabila Fatimah bercakap dengan dirinya (ingat, kita juga! Berlaku komunikasi enak di sini - intimasi - peribadi), bila dia bercakap dengan orang gajinya, suaminya. Ini kita dapat bandingkan dengan Rosnah yang sentiasa bercakap (di telefon) tetapi: all talk no value (rujuk dialog-dialog dalam filem Razak Mohaideen, contohnya). Kita tahu, apa-apa cakap yang datang daripada Rosnah tidak ada nilai. Ini dikuatkan dengan tindakannya nanti yang memang tidak bernilai (dan tidak dipedulikan pun oleh Fatimah). Fatimah pun, menyedari krisis sebenar dia dengan suaminya ialah komunikasi atau communication breakdown. Malah, pada babak klimaks inilah, sewaktu suaminya mula melakukan objektifikasi yang melulu (dan membadutkan dirinya!), Fatimah menyatakan kebenaran ini, terus-terang kepada suaminya: "Kita sudah tidak bercakap". Pada waktu itu, segalanya yang samar dan kabur, pecah, dipecahkan oleh tangisan kuat anak perempuan mereka yang bayi!
Perbandingan gerak dan imej ini mengancam: bayi diberikan fungsi terkuat di sini, mengembalikan kesiuman Mustaffa (tangisan budak itu sebenarnya tangisan sebenar Fatimah, malah sangat seksual dan jelas atas kemahuan batinnya yang tidak didengar). Oleh sebab itu, atas dasar keseimbangan komunikasi, dalam imej babak akhir filem ini yang sungguh memikat, kita melihat tiga wanita dan seorang lelaki. Dan entah mengapa, imej itu "sempurna", seimbang - sebuah komunikasi tercapai - sebuah filem menjadi penuh. Suhaimi jelas dalam hal ini: tradisi dan gerakan moden masyarakat Melayu-Malaysia sudah sedia asal bertumbuh dan kuat atas kehadiran sejarah dan peranan wanitanya dalam ruang rumah dan kemasyarakatannya. Ini suara politik Suhaimi yang paling jelas, mungkin tidak seantarabangsa atau sesofistikated Selubung atau Layar Lara, tetapi ia amat jelas dan kuat. Malah jauh lebih jujur dan ikhlas daripada Selubung atau Layar Lara.
Filem kecil ini memang mengagumkan apabila ditenung-tenung, dan paling mengejutkan, segala produksinya terletak baik pada tempatnya, termasuk runut bunyi dan skop sinematografinya. Lakonannya di kelas pertama dan sungguh mempesonakan, termasuk daripada watak-watak kecildan sampingannya. Kita akan terkejut dengan syot-syot yang terlihat mudah tetapi sungguh fungsional dan sampai; rujuk sahaja babak "melepaskan peluh" Mustaffa dan Kee Tuan Chye, apabila dengan sengaja, di atas kerusi, Mustaffa bertenggek - menampakkan kejantanannya (kuasa, dan tradisi seks) tetapi sekali gus menampakkan kelemahannya (vulnerability), dan ini dibuat bersahaja malah seakan main-main (kita lihat penanda Mustaffa melihat isu ini secara kaca mata yang kebudak-budakan, dan sememangnya itulah tindakan yang dilakukan selepas itu). Betapa, hal sekecil ini dijaga dengan ruwet dan baik oleh Suhaimi Baba.
Kita kini, mendambakan suatu penerusan suara wanita sebegini, dengan isu yang remeh sehari-hari tetapi berbekas. Antara yang terbaik daripada Suhaimi Baba dan oleh mana-mana pengarah wanita, dan aku percaya, tidak akan dilakukannya lagi atas desakan dan celoreng "komersialisme" yang diikutinya sekarang.